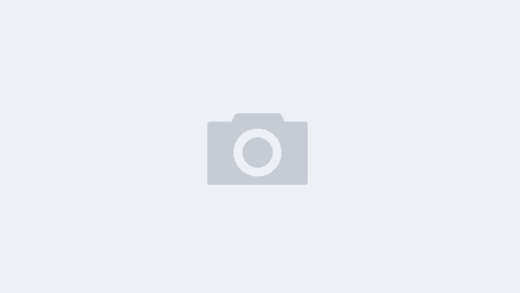[Artikel yang saya tulis ini pertama kali diterbitkan pada 18 Agustus 2019 di website BeritaBaik.id: https://beritabaik.id/read?editorialSlug=seni&slug=1566093383171-lebih-dekat-dengan-madura-di-pameran-nemor-southeast-monsoon]
Yogyakarta – Masyarakat Madura menyebut musim kemarau dengan ‘némor’. Secara harafiah, kata tersebut sebenarnya merujuk pada keberadaan angin muson timur (southeast monsoon) yang bergerak lamban sambil meniupkan suasana kering dan panas dari seberang lautan.
Saat bulan-bulan némor tiba, matahari bersinar sangat terik, tanah merengkah kering, dan lanskap berubah warna menjadi cokelat. Bagi penduduk Madura, némor dapat menjadi semacam pertanda baik bagi peladang untuk mulai menanam tembakau, bagi petani untuk memanen garam sebanyak-banyaknya, dan bagi para pelaut untuk mengarahkan kapal bergerak menyusuri arah barat.
Bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia, sebuah pameran kelompok bertajuk ‘NÉMOR, SOUTHEAST MONSOON’ dibuka di Cemeti Institute for Art and Society, Jl. DI Panjaitan No.41, Mantrijeron, Yogyakarta. Pengunjung dapat menikmati pameran ini secara cuma-cuma setiap harinya (kecuali hari Minggu dan Senin) pada jam 10.00-17.00 WIB, dari tanggal 17 Agustus-14 September 2019.
Pameran ‘NÉMOR, SOUTHEAST MONSOON’ berusaha membongkar dan menelaah kembali Madura sebagai sebuah wilayah psiko-geografis dan kultural dalam spektrum yang lebih luas. Seniman yang diundang setidaknya mewakili keragaman tersebut: sebagian berdomisili Madura, sebagian Madura diaspora, sebagian mewakili ‘Madura swasta’ (Pandalungan), sebagian lainnya adalah perupa non-Madura yang dapat memberikan pandangan lebih berjarak. Karya-karya yang dipamerkan mewakili empat kelompok narasi, yaitu sejarah, pesisir, tanah dan gender.
Selain tanah tegalan, kebudayaan Madura juga dibentuk oleh angin, gugusan kepulauan, tanah perantauan, mitos, involusi dan modernisasi yang terjadi terus menerus. Berbagai silang pengaruh itulah yang kemudian membentuk citra dan personalitas Madura yang distinctive, berbeda dari Jawa. Pandangan yang diwarisi sejak masa kolonial tersebut kemudian menjadi gestur yang umum saat ini, yakni melihat Madura dari kacamata Jawa.
Stereotip tersebut terus menerus dibuat dan dikonsumsi. Ironisnya, tak sedikit pula reproduksi citra yang pincang ini juga dilakukan oleh anak-anak muda Madura sendiri. Mereka membaca diri sendiri sebagai bagian dari artefak tua yang disimpan dalam lemari kaca, mengekalkan diri, seolah-olah Madura tidak mengalami perubahan dalam sendi-sendi kebudayaannya sendiri.
Pameran tersebut dikuratori oleh Ayos Purwoaji dan Shohifur Ridho’i, serta memajang karya-karya dari total 13 seniman: Anwari, Fakhita Madury, Fikril Akbar, FX Harsono, Hidayat Raharja, Ika Arista, Lutvan Hawari, Nindityo Adipurnomo, Rémi Decoster, Rifal Taufani, Syamsul Arifin, Suvi Wahyudianto, dan Tohjaya Tono. Seniman-seniman tersebut akan mewakili keragaman perspektif dalam menelaah kembali Madura dalam spektrum yang lebih luas dan menerjemahkannya menjadi bentuk karya yang beragam pula.
Pembukaan pameran dimulai pada Sabtu malam, dibuka dengan sebuah pertunjukan teatrikal ‘Bun Témor’ dari Anwari dan teman-teman. Anwari adalah seorang sutradara dan teaterwan yang berasal dari Sumenep. Bertolak dari pendekatan dan pengamatan terhadap gestur tubuh keseharian masyarakat di kampung halamannya, Anwari menciptakan pertunjukan ‘Bun Témor’ yang berarti ‘(tanah) bagian timur’ dengan cara menegaskan kehadiran nilai-nilai pada material di dalam kultur petani, seperti sapi, kandang, batu, tanah, tikar, pandan, cangkul, sarung, dan sebagainya.
Ia juga kerap melibatkan keluarga dan tetangga dekatnya ke dalam karya-karya pertunjukannya untuk menajamkan ‘daya hadir’ mereka sebagai subjek kebudayaan. Materialitas yang tumbuh dari ruang dan waktu spesifik (dengan seluruh lanskap sosialnya) tidak hanya memiliki kualitas representasi atas kampung halaman, namun juga titik tolak pembayangan atas kampung/tanah di masa depan.
Setelah pertunjukan ‘Bun Témor’ berakhir, pengunjung dipersilakan pindah dari ruang utama pameran dan menempatkan diri ke area taman untuk menyaksikan pagelaran musik ‘Akar Suara’ dari Lutvan Hawari, seorang komposer serta penata musik yang lahir di Sumenep. Lutfan Hawari mencoba mengidentifikasi pengalaman ‘bunyi’ yang pernah ia lihat dan alami langsung di Madura dan Jawa dengan berangkat dari pertanyaan-pertanyaan seperti ‘Apakah Madura dan Jawa bisa setara? Apakah mungkin kita dapat berpikir dengan melampaui cara pikir dikotomis? Bukankah Madura dan Jawa saling berjejalin?’.
Saat ini Lutvan tinggal di Bondowoso, satu wilayah ‘Tapal Kuda’, di mana masyarakat Madura dan Jawa bertemu dan hidup bersama. Di dalam kultur ‘antara’ itulah Lutvan memasuki tegangan Madura-Jawa sebagai kategori pengetahuan yang dialektis dan dapat disejajarkan dan sekaligus meleburkannya menjadi satu komposisi yang (bayangan idealnya) non-dikotomis. Ini adalah sebuah percobaan spekulatif dan wahana eksperimental melalui alat musik cakjeng yang ia ciptakan sendiri, yang dijajarkan dengan unsur bunyi dari musik elektronik.
Pameran ini juga akan mengadakan agenda tambahan dalam waktu dekat, seperti program seniman wicara dan pergelaran musik ‘Ngongghâin’ oleh Rifal Taufani ft. Erwin Oktaviyan pada tanggal 20 Agustus 2019 pukul 15.00 WIB, serta mengadakan program kurator wicara pada tanggal 13 September 2019 pukul 15.00 WIB.
Foto: Hanni Prameswari E.