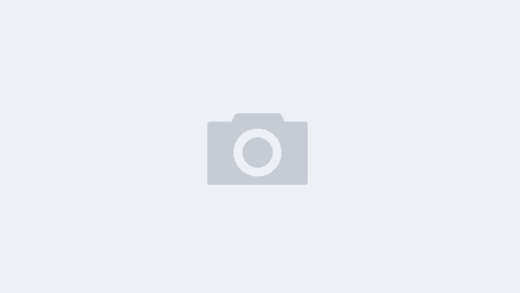[Tulisan saya ini pertama kali diterbitkan pada 24 Oktober 2019 di website BeritaBaik.id: https://beritabaik.id/read?editorialSlug=gallery-foto&slug=1571886778377-melihat-potret-pinggiran-asia-tenggara-di-biennale-jogja]
Yogyakarta – Perhelatan besar seni rupa Biennale Jogja yang dilaksanakan setiap dua tahun, kembali hadir tahun ini. Biennale Jogja XV Equator #5 diselenggarakan selama tanggal 20 Oktober – 30 November 2019 pada pukul 10.00 – 21.00 WIB, gratis dan terbuka untuk umum, serta bertempat di 5 lokasi yang berbeda, yakni Jogja National Museum, Taman Budaya Yogyakarta, Gedung PKKH UGM, Jalan Ketandan Kulon 17, dan Kampung Jogoyudan.
Sejak tahun 2011, perhelatan yang diorganisasi oleh Yayasan Biennale Yogyakarta (YBY) ini berangkat dari sebuah tema besar, yakni “equator” atau khatulistiwa. Rangkaian biennale ini mematok batasan geografis tertentu di planet bumi, yaitu kawasan yang terentang di antara 23.27 Lintang Utara (LU) dan 23.27 Lintang Selatan (LS).
Dalam pengantar Biennale Jogja XV Equator #5 2019 yang ditulis oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, tema ‘Do We Live in The Same Playground?’ dipilih untuk merangkum inspirasi seniman-seniman yang terlibat dalam menafsirkan segelintir persoalan-persoalan “pinggiran” yang terjadi di seantero Asia Tenggara. Permasalahan-permasalahan seperti identitas (gender, ras, dan agama), narasi-narasi kecil/alternatif, konflik sosial-politik, liminalitas, perburuhan, lingkungan, atau lebih spesifik lagi, praktik kesenian yang diabaikan. Akiq AW, Arham Rahman, dan Penwadee Nophaket pun didapuk sebagai tim kurator dalam pameran kali ini.
Pada hari Rabu (23/10) malam, BeritaBaik berkunjung ke salah satu lokasi yang menjadi pameran utama Biennale Jogja XV Equator #5, yaitu Jogja National Museum yang beralamat di Jalan Prof. DR. Ki Amri Yahya No.1, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta.
Terdapat karya-karya dari 42 seniman dari berbagai wilayah di Asia Tenggara yang bisa kita saksikan di bangunan yang terbagi dalam tiga lantai ini.
Ada beberapa karya yang menurut kami sangat menarik dan cukup mencuri perhatian. Di lantai dasar, kami sungguh terpesona dengan karya dari Ling Quisumbing Ramilo berjudul ‘Forest for The Tries: Peri-Peri Library’ yang menampilkan instalasi perpustakaan yang seluruhnya terbuat dari potongan-potongan kayu. Di lantai kedua, proyek lokakarya kolase berjudul ‘Kata Untuk Perempuan’ dari Ika Vantiani sungguh memanjakan mata dengan segala warna-warninya.
Kemudian di lantai tiga, kami tertarik dengan karya dari Ridwan Alimuddin yang merespons persoalan pelik di Desa Pambusuang, Sulawesi Barat tentang sampah-sampah yang dibuang di laut dengan menghadirkan instalasi alat jemuran ikan terbang lengkap dengan telur ikan terbang yang layak konsumsi dan yang telah bercampur dengan mikro-plastik, dan tentu saja karya dari Citra Sasmita yang mencoba menghadirkan sebuah konteks baru, merekonstruksi narasi historis dan membuat tokoh perempuan menjadi pusat penceritaannya, sehingga sisi heroik dan protagonis yang selama ini ditampilkan melalui perspektif maskulin, dapat dilihat ulang melalui perspektif yang berbeda.